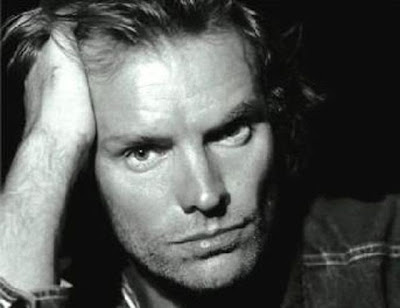Penulisan otobiografi oleh
seorang yang berprofesi penulis memiliki kelebihan. Terutama dalam kemahirannya
memainkan bahasa, serta kecenderungan untuk menyajikan “kebenaran” secara
imbang. Ia tak pernah malu-malu bercerita perihal kekeliruan dan kesalahan.
Memoar tidak lagi sebatas album kenangan. Buku Wartawan Jadi Pendeta (2013) karya Putu Setia menampilkan uraian
kisah tanpa terpusat pada pengupasan cerita semata.
Kisah ini menggugah
tanpa terjerat label “biografi inspiratif”. Dilahirkan dari keluarga
berkecukupan namun terjungkal dalam kemiskinan. Berawal dari tabiat sang ayah
yang gemar berjudi, beberapa hektar tanah sawah dan kebun kopi pun ludes
digerogoti rentenir. Konon, kemiskinan itu disebabkan pula oleh karma buruk
keluarga karena menolak kewajiban menjadi pemangku: pemimpin upacara ritual di
sebuah pura. Penulis memang lahir dan tumbuh di sebuah dusun dengan ketaatan
tinggi kepada adat dan agama Hindu. Penolakan itu pun berbuah “vonis” dari
masyarakat: rezeki seret dan miskin (hlm.16).
 Kemiskinan merenggut harapan
menunaikan sekolah menengah atas hingga khatam. Penulis mengenang masa-masa
mengharukan saat baju seragam sekolahnya dijual sang ibu demi membeli makanan. Putu
kecil pasrah. Betapa malunya tak bisa makan di Hari Raya Galungan (hlm.144).
Impian bersekolah kandas demi urusan perut keluarganya. Namun, kegagalan
meneruskan sekolah tidak membuat semangat hidup penulis tamat.
Kemiskinan merenggut harapan
menunaikan sekolah menengah atas hingga khatam. Penulis mengenang masa-masa
mengharukan saat baju seragam sekolahnya dijual sang ibu demi membeli makanan. Putu
kecil pasrah. Betapa malunya tak bisa makan di Hari Raya Galungan (hlm.144).
Impian bersekolah kandas demi urusan perut keluarganya. Namun, kegagalan
meneruskan sekolah tidak membuat semangat hidup penulis tamat.
Kehidupan jalan terus.
Penulis memutuskan pergi ke kota, mengadu nasib tanpa ijasah. Ia nekad melamar
pekerjaan. Bisa dibayangkan, meminang pekerjaan tanpa ijasah. Keberanian itu
menuai hasil, penulis diterima bekerja sebagai tukang gambar di Perusahaan
Listrik Negara (PLN) sembari rutin menulis cerita pendek untuk dikirim ke
koran. Ketekunan menulis justru kian menguat. Ia keluar dari pekerjaan demi fokus
menekuni kepenulisan: jadi wartawan dan cerpenis.
Sungguh keputusan yang
tepat. Karir wartawan kian moncer. Dari harian Angkatan Bersenjata edisi Nusa Tenggara hingga akhirnya diterima di
majalah Tempo, tidak satu pun urusan
ijasah/karir pendidikan mengganjal perjalanan karir penulis. Diterima tanpa
pertanyaan jenjang pendidikan. “Keajaiban apakah yang ada pada seorang Putu
Setia dalam meniti karirnya sebagai wartawan, kok bisa tanpa melamar?” Ya, saya
tak pernah melamar, karena memang takut melamar. Ditanya soal ini soal itu,
terutama pendidikan, apa yang harus saya jawab?”(hlm. 283). Putus sekolah memberi
beban psikologis berkepanjangan bagi penulis. Hidup diliputi keminderan. Ia
kerap disergap cemas yang hebat ketika berhadapan dengan pertanyaan jenjang
pendidikan.
Kala masa jabatan
sebagai Ketua Umum Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI) berakhir setelah
dua kali menjabat (1991-1995, 1995-1999), rasa gundah itu kembali menguasai
pikirannya. “Tiba-tiba saya merasa sudah membohongi banyak orang, bagaimana
mungkin orang “berpendidikan rendah” harus memimpin dan menggerakkan roda
organisasi para intelektual? (hlm. 374). Meski penulis memahami, cendekiawan
tidak diukur dari pendidikan formalnya. Belenggu “status pendidikan” terlanjur
menancap di jiwa seorang Putu Setia.
Demikian pula saat berlangsung
ritual penobatan pendeta. Pidato Ketua Parisada Dharma Provinsi Bali, I Gusti
Ngurah Sudiana saat penyambutan pendeta baru membuat penulis gamang tak karuan.
Pidato panjang itu mengulas tentang maraknya pendeta yang lahir dari kalangan
sarjana, S2, S3, hingga profesor. “Ingin rasanya saya mengambil mic yang dipakai berpidato itu, dan saya
umumkan kepada hadirin bahwa pendeta yang lahir nanti adalah pendeta yang tak
punya ijasah SMA , pendeta yang hanya lulusan SMP.” (hlm. 381).
Bagi Putu Setia, tekad menunaikan
“utang” keluarga memang sudah begitu bulat. Karir sukses dan nasib baik diyakini
buah dari kesediaan penulis menunaikan kewajiban keluarga sebagai pemangku. Tidak
tanggung-tanggung, tidak hanya menjadi pemangku, penulis sekaligus hendak
menjadi pendeta: gelar keagamaan tertinggi dalam umat Hindu!
Bagaimana mungkin
seseorang yang tidak lulus sekolah menengah atas bisa menyandang gelar pendeta?
Inilah pencapaian tertinggi dalam hidup Ida Pandita Mpu Jaya Prema (nama Putu
Setia setelah dinobatkan jadi pendeta). Sebuah lakon panjang tentang keyakinan
dan keberuntungan. Benar bila Goenawan Mohamad dalam pengantar menganggap buku
ini merupakan sebuah ucapan rasa syukur dan sekaligus rasa berutang—dan penanggungan
jawab mengapa itu perlu.
Kemampuan penulis dalam
mendeskripsikan kisahnya tak perlu diragukan. Namun, bagi pembaca yang
mengikuti tulisannya di koran, buku ini terasa jauh dari kesan eksentrik. Cita
rasa humor memang masih bisa pembaca rasakan. Hanya saja, dalam merespons
setiap momen-momen hidupnya, tidak ada taburan kata penuh kritik ataupun satire
tajam yang biasa penulis ungkapkan dalam setiap tulisannya. Buku ini hanya sebuah “penanggungan jawab”
dan ungkapan kebersyukuran penulis atas hidup yang penuh keberuntungan. Lain,
tidak.